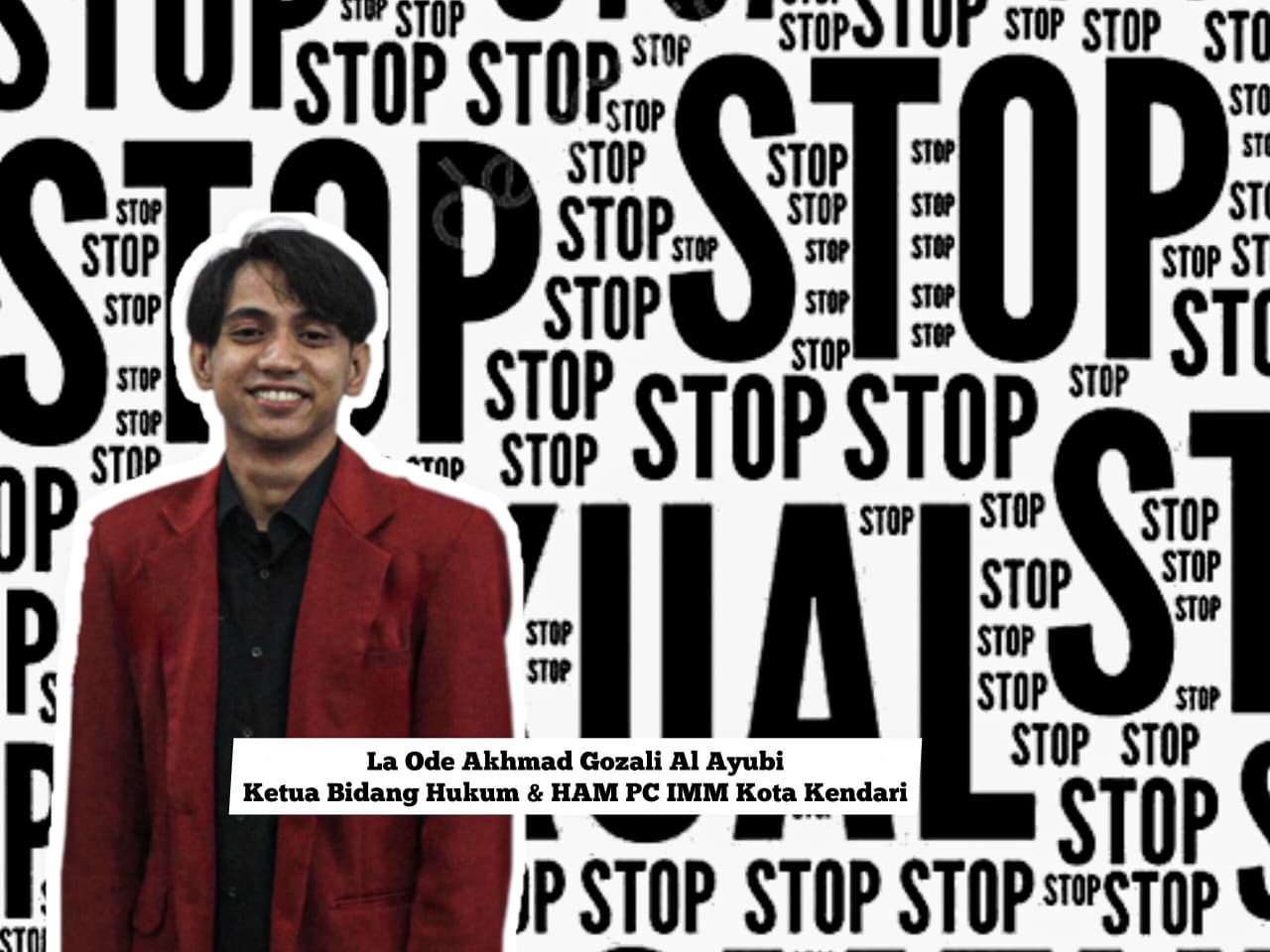Oleh; La Ode Akhmad Gozali Al Ayubi ( Ketua PC IMM Kota Kendari Bidang Hukum Dan HAM )
Pelecehan seksual di kalangan mahasiswa merupakan masalah serius yang sering kali dipandang sebelah mata. Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu, namun realitas menunjukkan banyak kasus pelecehan justru terjadi di dalamnya, baik oleh sesama mahasiswa, senior, bahkan dosen. Fenomena ini ibarat gunung es yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil, sementara banyak korban memilih diam karena takut akan stigma, intimidasi, atau tidak percaya pada mekanisme penanganan kampus.
Pelecehan seksual bukan hanya persoalan moralitas individu, melainkan juga kegagalan sistemik. Kampus kerap lebih mementingkan citra institusi ketimbang keberanian untuk mengungkap kasus. Alih-alih melindungi korban, beberapa kampus justru membungkam mereka dengan dalih menjaga nama baik. Ini jelas sebuah ironi, lembaga pendidikan yang semestinya mencerdaskan, justru membiarkan praktik kekerasan berbasis gender berlangsung tanpa konsekuensi tegas.
Lebih parah lagi, ada budaya patriarki yang mengakar dalam lingkungan mahasiswa. Senioritas, hubungan kuasa antara dosen dan mahasiswa, hingga pergaulan bebas tanpa pemahaman batas consent (persetujuan), membuat kasus pelecehan dianggap lumrah atau bahkan dilecehkan kembali melalui candaan. Korban sering dipaksa menerima anggapan bahwa “pelecehan adalah risiko menjadi mahasiswa,” padahal ini bentuk normalisasi kekerasan.
Pelecehan seksual bukan sekadar “kesalahan kecil” yang bisa diselesaikan dengan damai atau permintaan maaf. Ini adalah bentuk kekerasan yang merampas hak korban atas rasa aman, martabat, dan kesehatan mental. Secara hukum, tindakan pelecehan seksual sudah diatur dalam KUHP, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hingga UU Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya, tidak ada alasan bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum hanya karena kasusnya terjadi di lingkungan kampus.
Namun, problem besarnya ada pada penegakan hukum. Banyak kasus pelecehan di kampus yang dipaksa selesai secara “kekeluargaan” dengan alasan menjaga reputasi institusi. Padahal, praktik ini adalah bentuk pembungkaman korban dan secara hukum merupakan penghalangan proses keadilan. Jika kampus atau pihak internal dengan sengaja menutup-nutupi kasus, maka secara kritis dapat dipandang sebagai “obstruction of justice” yang justru memperburuk posisi hukum lembaga tersebut.
Kampus seharusnya menjadi pihak pertama yang mendorong korban untuk melapor, memberikan pendampingan psikologis maupun hukum, serta menindak tegas pelaku melalui mekanisme disiplin internal tanpa menafikan proses pidana di kepolisian. Tidak ada satupun aturan yang membenarkan kampus menutup-nutupi kasus, apalagi menyalahkan korban.
Mahasiswa juga dituntut untuk lebih kritis. Sebagai kaum intelektual muda, mereka seharusnya menjadi garda depan melawan pelecehan seksual, bukan justru menjadi pelaku atau pembela pelaku. Gerakan solidaritas mahasiswa harus hidup, mendorong terciptanya budaya kampus yang sehat, berkeadilan, dan menghargai tubuh serta martabat setiap individu.
Pada akhirnya, kampus yang membiarkan pelecehan seksual berarti gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat peradaban. Jika dunia akademik masih menutup mata terhadap kekerasan ini, maka gelar dan pengetahuan yang diklaimnya hanya akan menjadi topeng bagi kebobrokan moral dan pelanggaran hukum yang dibiarkan tumbuh di dalamnya.